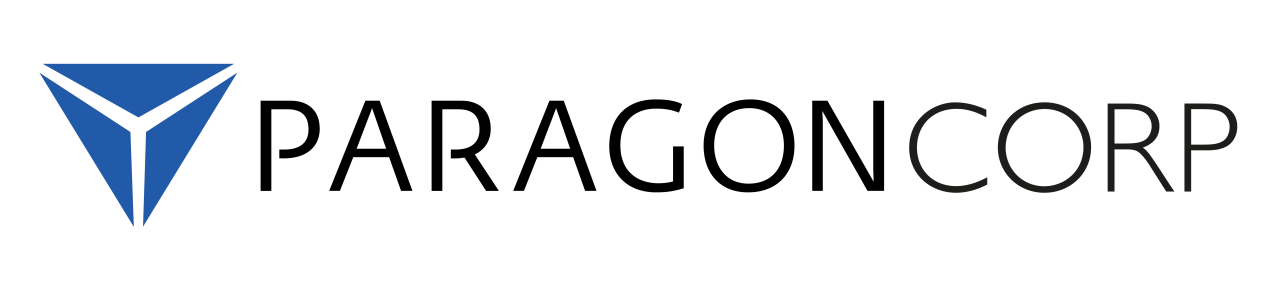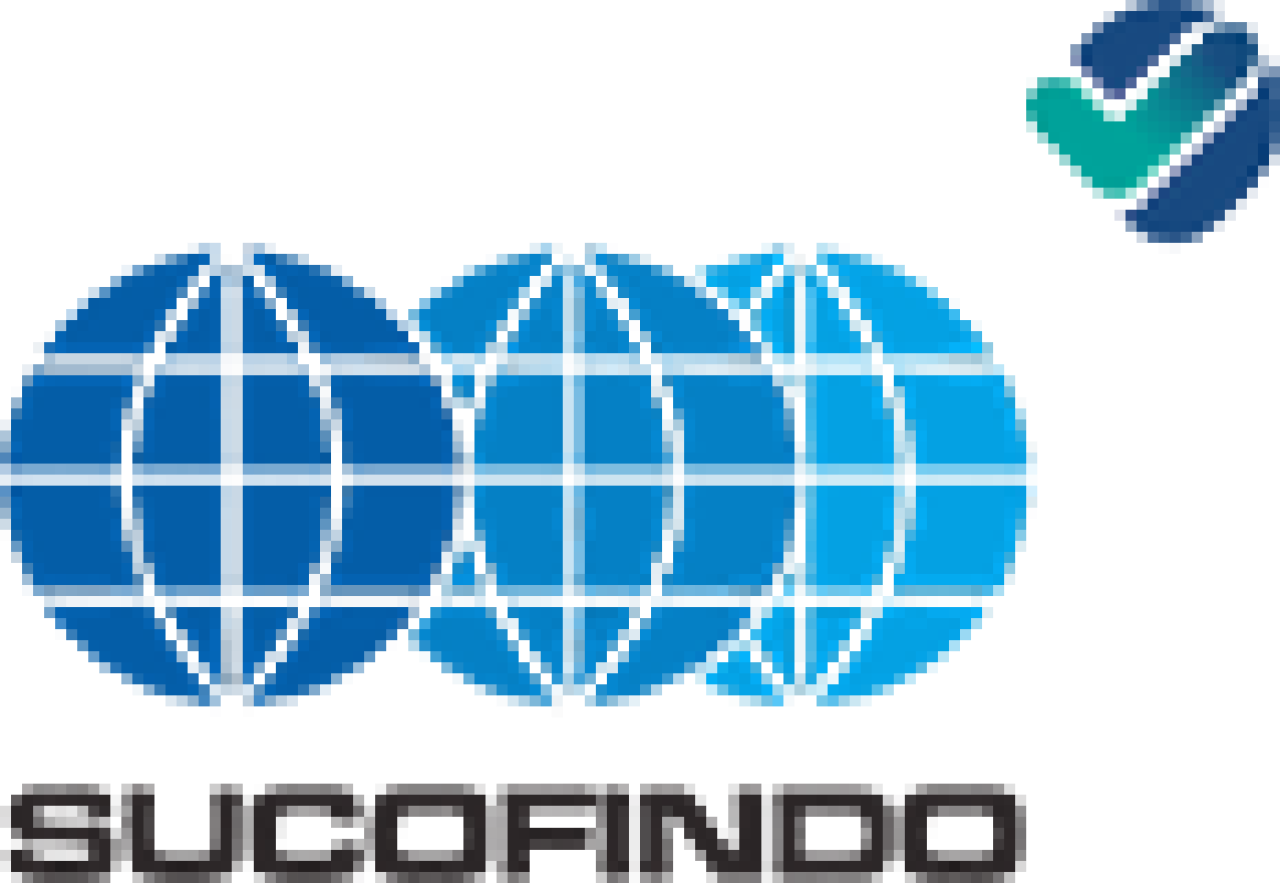Oleh: Adrian Perkasa (Dosen Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga; Peneliti Doktoral Universiteit Leiden negeri Belanda)
Optika.id - Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda, kembali meminta maaf secara resmi kepada bekas koloninya. Kali ini atas nama pemerintah Belanda, permohonan maaf disampaikan untuk tujuh daerah yakni di Karibia atas terjadinya perbudakan selama 250 tahun di masa lalu.
Ketujuh daerah tersebut yakni Suriname, Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Saba dan Sint Eustatius. Permintaan maaf tersebut merupakan tindak lanjut pemerintah Belanda atas dirilisnya hasil penelitian Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden atau Dewan Penasihat Kelompok Dialog Sejarah Perbudakan.
Dewan Penasihat tersebut dibentuk pada tahun 2020 oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Dalam Negeri Belanda. Pembentukan Dewan Penasihat ini merupakan langkah konkrit dari pemerintahan Mark Rutte atas serangkaian tuntutan permintaan maaf kepada negara-negara bekas penjajah atas perbudakan di masa penjajahan.
Susunan anggota Dewan Penasihat ini juga beragam mulai dari Lilian Gonçalves-Ho yang berlatar belakang advokat dan juga ketua Dewan Penasihat untuk urusan restitusi warisan budaya sampai Edgar Davids seorang pensiunan pemain sepabola kondang keturunan Suriname.
Pemerintah Belanda memutuskan untuk melakukan pengkajian yang mendalam atas dinamika perbudakan sampai dihapuskannya secara resmi pada tahun 1863. Tidak hanya sampai di situ, mereka juga meminta kepada Dewan Penasihat untuk mengkaji warisan dari perbudakan terhadap kondisi sosial masyarakat hari ini.
Sebenarnya penelitian akademis terkait perbudakan terkait topik perbudakan khususnya dalam lingkup transatlantik telah banyak dilakukan. Buku terkait kondisi perbudakan pun juga telah banyak beredar, salah satu yang paling berpengaruh adalah karya Anton de Kom, Wij Slaven van Suriname atau Kami Budak dari Suriname pada 1934 dan diterbitkan ulang tanpa sensor pada 1971. Buku ini bisa dibilang memiliki efek bagi publik Belanda seperti novel Max Havelaar karya Multatuli pada awal abad XX.
Selain dari karya-karya tulis, tuntutan agar Pemerintah Belanda meminta maaf telah datang setidaknya sejak tahun 1995. Seorang warga keturunan Suriname membuat surat terbuka kepada pemerintah untuk meminta maaf atas perbudakan di masa lalu.
Meski tidak langsung mendapat respon, isu ini mulai mendapat perhatian di publik Belanda. Sejak tahun 2001 hingga 2013, terdapat permintaan maaf secara sporadis dari berbagai kalangan, khususnya dari para politisi partai-partai progresif yang menduduki jabatan penting di pemerintahan.
Rupanya isu perbudakan kembali tereskalasi seiring dengan isu Black Lives Matter maupun tekanan untuk melakukan repatriasi warisan-warisan budaya dari tanah jajahan di Eropa. Selain menjadi isu utama di parlemen, berbagai pihak mulai dari pemerintahan di tingkat lokal sampai swasta mulai merespon masalah perbudakan ini.
Diawali dari Walikota Amsterdam, berbagai pemerintah kota besar lain seperti Rotterdam dan Den Haag telah menyampaikan permintaan maaf atas perbudakan di masa lalu. Kemudian Bank Sentral Belanda dan bank ABN-AMRO juga menyusul memohon maaf karena eratnya keterlibatan lembaga ini dalam sejarah perbudakan.
Tentu saja perkembangan isu perbudakan tadi disimak dengan seksama oleh Perdana Menteri Mark Rutte, yang juga merupakan seorang sejarawan lulusan Universitas Leiden. Oleh karena itu, ketika hasil penelitian Dewan Penasihat dirilis, Rutte segera mengambil sikap dengan melakukan penyampaian permohonan maaf secara resmi mewakili Pemerintah Belanda.
Meski masih menyisakan ketidakpuasan bagi sejumlah kalangan di Belanda, Mark Rutte beserta kabinetnya memutuskan untuk melakukan serangkaian misi permintaan maaf sejak awal Desember 2022
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mark Rutte memilih untuk menyampaikan permohonan maafnya di gedung Arsip Nasional Belanda. Pemilihan tempat ini sendiri bukannya tanpa alasan mengingat berbagai fakta historis maupun memori kolektif terkait perbudakan banyak tersimpan dalam tumpukan-tumpukan arsip, baik yang telah dimanfaatkan untuk penelitian maupun menunggu untuk dijadikan riset-riset selanjutnya.
Selain itu, delapan menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini juga melakukan lawatan resmi ke tujuh daerah di Karibia tadi dalam rangkaian permintaan maaf Belanda.
Bagaimana Indonesia?
Permintaan maaf Pemerintah Belanda atas perbudakan di masa lalu rupanya juga mendapat respon dari publik Indonesia. Tentu saja selain sejarah panjang antar kedua bangsa ini dari masa kolonial, bisa jadi permintaan maaf yang disampaikan oleh Pemerintah Belanda atas kekerasan selama masa Revolusi juga mempengaruhi perhatian tersebut. Lantas dimanakah posisi Indonesia atas permintaan maaf Belanda kali ini?
Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa permintaan maaf atas perbudakan masa lalu dari Pemerintah Belanda hanya terbatas pada apa yang terjadi di Karibia atau perbudakan Transatlantik. Namun bukan berarti bahwa pihak Belanda menutup mata atas perbudakan yang terjadi pada masa penjajahan di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pidato resmi Mark Rutte, Pemerintah Belanda menyadari bahwa perbudakan juga terjadi di belahan dunia Timur dimana bangsa Belanda juga ikut bertanggung jawab di sana khususnya atas apa yang terjadi di nusantara.
Di sinilah terbuka kesempatan bagi pihak Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban Belanda atas proses perbudaakan di masa lalu. Seperti halnya yang digarisbawahi oleh Rutte sendiri bahwa permohonan maaf atas perbudakan di Karibia bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah koma dalam rangkaian untaian kalimat. Artinya, masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di masa depan dalam mempertanggungjawabkan masa lalu yang kelam.
Hatta, permintaan maaf Belanda harus dilihat bukan sebagai akhir namun sebuah langkah awal dalam upaya penyelesaian konflik di masa lalu. Kita sebagai bangsa Indonesia harus segera tanggap merespon pernyataan permohonan maaf pemerintah Belanda baik atas kekerasan selama Revolusi maupun perbudakan ini. Bisa saja pihak Indonesia meminta kompensasi jangka pendek misalnya finansial, seperti salah satu rencana dari Pemerintah Belanda terhadap daerah-daerah Karibia, ataupun jangka panjang dengan menyuarakan aspirasi berbagai pihak yang berkepentingan di Indonesia.
Hanya saja untuk menentukan dasar tuntutan permintaan maaf berikut kompensasinya, harus diakui perlu langkah besar seperti halnya yang diambil Pemerintah Belanda. Mereka mengambil pijakan dalam meminta maaf melalui dasar masukan berupa hasil kajian dari ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dari komite yang anggotanya mewakili beragam kepentingan. Petanyaannya, apakah Pemerintah Indonesia berani mengambil langkah semacam ini?
Meninjau kembali sejarah seperti halnya yang dilakukan Pemerintah Belanda harus diakui bukanlah perkara yang mudah. Selain menemukan berbagai fakta baru, bisa jadi banyak sekali pemahaman sejarah yang harus direvisi. Sebagai contoh misalnya terkait isu perbudakan di masa kolonial.
Pernahkah kita mendengar kisah seorang budak yang bernama Dandayu? Atau lebih umum lagi adakah satu bab di pelajaran sejarah yang kita dapatkan di bangku sekolah bagaimana proses perbudakan di Indonesia berlangsung hingga dihapuskannya oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1860 atau 3 tahun sebelum peraturan yang sama diberlakukan untuk daerah koloni Belanda di Karibia?
Bisa jadi langkah untuk membuka kembali lembaran masa lalu bangsa Indonesia menimbulkan banyak pro dan kontra dalam publik Indonesia sendiri. Apalagi narasi sejarah Indonesia, khususnya sebagai salah satu mata pelajaran, hanya mengenal satu narasi sejarah kanonikal dimana narasi sejarah yang berbeda kerap dianggap membelokkan sejarah. Namun bisa jadi justru dengan kembali melakukan pengamatan yang cermat, kepala dingin, dan kritis atas masa lalu, banyak sekali pelajaran yang bermanfaat bagi masa depan bangsa ini.
Editor : Pahlevi