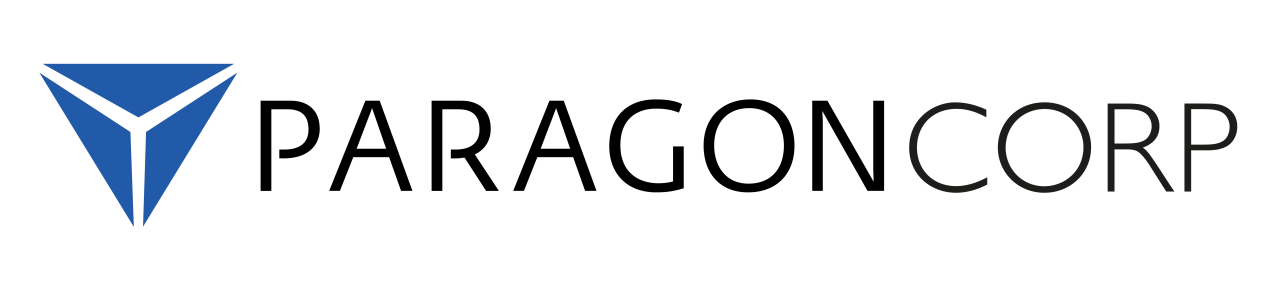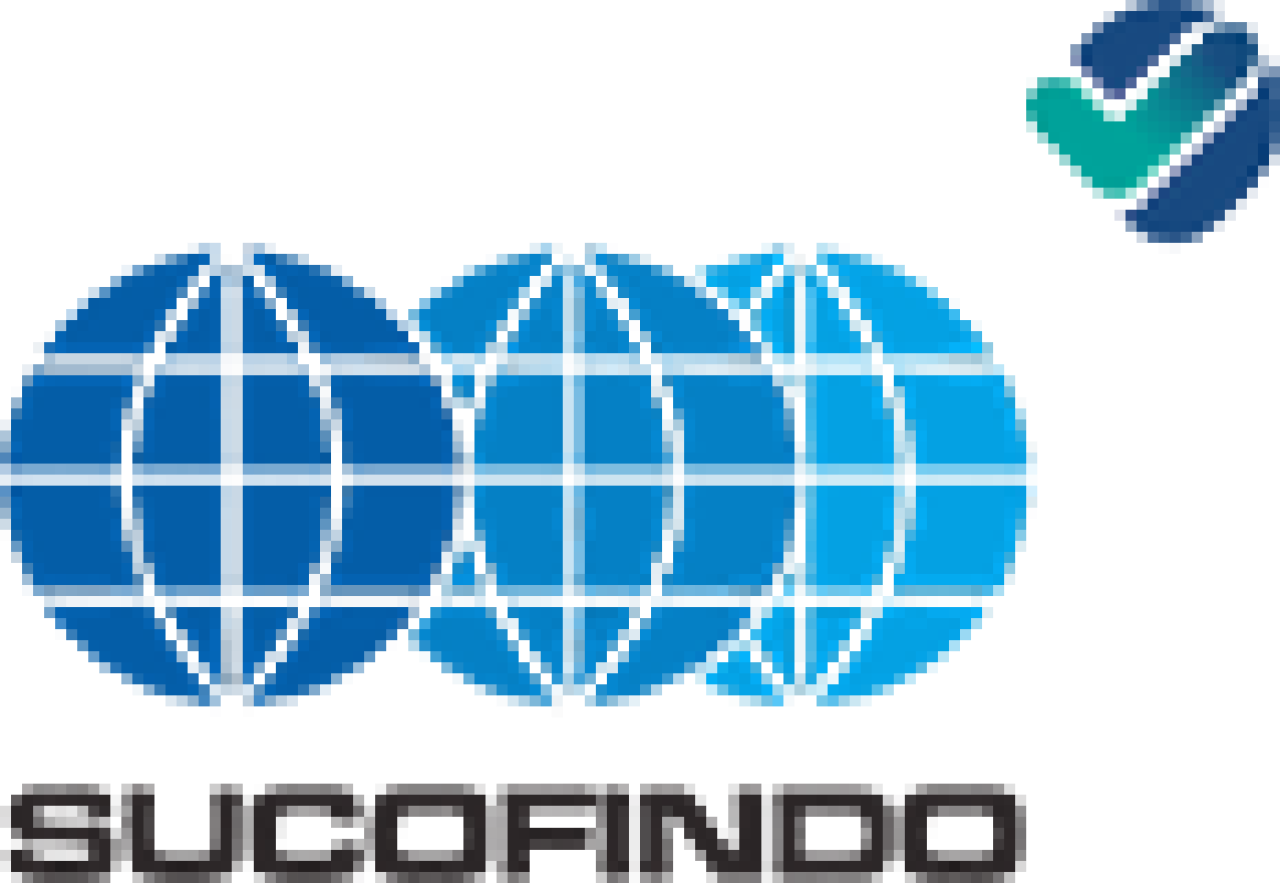[caption id="attachment_19035" align="aligncenter" width="150"] Ruby Kay[/caption]
Ruby Kay[/caption]
Optika.id Entah kenapa banyak orang yang benci setengah mati dengan politik identitas yang berlaku di Indonesia. Ia dianggap bisa membuat sekat, jarak, batas hingga menciptakan perpecahan. Apa memang selalu seperti itu? Padahal para pelaku kegiatan politik di semua negara yang menerapkan sistem demokrasi pasti melakukan politik identitas.
Baca Juga: Politik Identitas Sebenarnya Adalah Hal yang Wajar
Sejak melaksanakan pemilu tahun 1955, negeri ini sudah menerapkan politik identitas. Kalangan nasionalis mendirikan PNI, muslim moderat religius membentuk Masyumi, nahdliyin mendirikan partai NU, ummat protestan membuat Partai Kristen Indonesia, wong Katholik buat partai Katholik, sing berideologi marxist mendirikan PKI. Yang begitu apa gak disebut politik identitas?
Mesti dipahami kalau politik identitas itu tak selamanya buruk. Seorang politisi dalam kontestasi Pemilu pasti membawa identitas agama, suku, ras, golongan, trah. Apakah itu salah? Selama tidak menggaungkan kebencian, sah-sah saja.
Berikut beberapa contoh penerapan politik identitas:
Caleg bernama Asep, Drajat, Atmadja berusaha menonjolkan keaslian sundanya untuk menarik simpati masyarakat dibumi parahyangan. Masak kalah sama Adian Napitupulu. Walau bukan orang sunda tapi ia bisa terpilih jadi legislator dari daerah pemilihan di Jawa Barat.
Begitu pula dengan Manurung, Sianipar, Hutapea. Mereka akan berjuang sekuat tenaga merebut suara orang batak di Sumatera Utara.
Di Bali, tiap calon gubernur menonjolkan identitas kehinduannya. Mulai mereka mengungkap kasta, si A turunan brahmana, si B ksatria, si C waisya. Masing-masing kontestan juga berusaha meraih simpati publik dengan mengusung program yang akan melindungi dan memelihara tradisi ummat Hindu Bali.
Di kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, tiap calon bupati akan merasa paling protestan. Yang semula jarang menghadiri kebaktian di gereja, mendadak jadi sering ikut misa, silaturahmi ke pendeta. Yang tadinya gak taat, tiba-tiba mengenakan kalung salib segede gaban agar terlihat religius. Bisa dimaklumi, karena 93% penduduk Minahasa beragam kristen protestan dan katholik.
Di kota Singkawang, Kalimantan Barat, calon walikota bernama Herman Wijaya yang sejatinya lahir, besar dan sehari-harinya berdomisili di Jakarta, mendadak menonjolkan nama tionghoanya, Lee Tjae Wei. Saat kampanye dan blusukan, ia sebisa mungkin menghilangkan logat anak gaul Jaksel, lalu mulai berbahasa Tio Ciu campur dialek melayu.
Cut Zahara cuma numpang lahir di serambi Mekkah, besar di Jakarta, kuliah diluar negeri. Saat nyaleg dari dapil di Aceh, mendadak ia memakai hijab, menutup rapat aurat. Padahal sebelum nyaleg, tiap week end suka dugem di Kemang pakai celana pendek.
Di pulau Madura, politik identitas trah (genetis) masih kental terasa. Caleg yang memiliki garis keturunan dengan habaib atau kyai ternama, biasanya akan jadi idola, berpotensi memenangkan kontestasi pileg atau pemilukada.
Di kabupaten atau provinsi yang komposisi agama dan sukunya nyaris berimbang, cabup muslim bisa jadi akan berpasangan dengan cawabup beragama katholik. Cawali etnis tionghoa, wakilnya orang jawa atau melayu. Strategi politik macam begini biasanya karena faktor statistik demografis.
Beberapa contoh diatas merupakan seni bermain politik identitas. Selama tidak mendiskreditkan entitas yang lain, namun hanya untuk menonjolkan jati diri dan keunikannya sendiri, why not?
IMHO, politik identitas di Indonesia saat ini masih tergolong positif. Dilakukan demi menghimpun simpati publik, bukan untuk membuat konflik. Celakanya, banyak analis politik yang menjadikan negara maju sebagai contoh penerapan demokrasi yang ideal.
Barusan gue melihat cuplikan video podcast Najwa Shihab. Ia memuji demokrasi di Perancis yang menurutnya berjalan dengan baik. Alasannya sederhana, karena capres di Perancis beragam, rakyat jadi banyak pilihan. Gak seperti di Indonesia yang sejak reformasi bergulir, capresnya cuma 2, 3 maksimal 5 pasang.
Baca Juga: Misi Menyelamatkan Perancis
Dalam hal ini, gue berani berbeda pendapat dengan presenter ternama itu. Capres di Perancis awalnya memang berjumlah 12 orang. Tapi ujung-ujungnya yang masuk keputaran kedua toh cuma 2 orang, Emmanuel Macron dan Marine Le Pen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Najwa Shihab juga harus tahu kalau prosentase golput di Pilpres Perancis tahun 2022 ini menjadi yang terbesar sejak tahun 2002, yaitu mencapai 26,31%.
Fakta berikutnya adalah sebanyak 543.609 surat suara dibiarkan pemilih kosong melompong. Padahal rakyat Perancis sudah disodori banyak pilihan, nyatanya prosentase golput dan surat suara cacat tetap saja masih banyak.
Ini membuktikan bahwa Presidential Threshold 0% pun tidak menjamin bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Disodori banyak pilihan kandidat capres bukan berarti pemilih lalu berbondong-bondong mendatangi tempat pemungutan suara.
Itu semua terjadi di Perancis yang secara infrastruktur dan knowledge politik masyarakatnya tergolong mapan. Pertanyaannya sekarang, adakah pihak yang bisa menjamin kalau diberlakukan presidential threshold 0% maka partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 akan meningkat drastis? Jika menjawab ya, coba uraikan secara sistematis, kita bedah dan analisa bersama.
Yang jelas, PT 0lum tentu meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Tapi sudah pasti menambah cost politik, otomatis membebani keuangan Negara.
Lebih lanjut, Najwa Shihab hendaknya jangan mengukur diri dengan negara maju terus dong. Padahal sebagai sebuah bangsa, kita ini punya keunikan berpolitik yang tidak dimiliki bangsa lain. Yup, moral dan etika ketimuran, budaya unggah-ungguh yang sampai sekarang masih dipertahankan. Itulah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia.
Kalau mau objektif, justru di negara-negara sekuler politik identitas dimainkan secara brutal. Contoh konkritnya ya pemilihan presiden Perancis bulan april lalu. Dalam sesi debat capres, Marine Le Pen tak segan mengungkap kebenciannya terhadap syariat Islam. Ia bahkan berjanji dan berkata dengan lantang jika terpilih sebagai presiden akan melarang penggunaan jilbab ditempat umum. Baginya, jilbab merupakan simbol pengekangan, wujud radikalisme, bisa menyuburkan benih-benih terorisme. Gila gak tuh?
Baca Juga: Misinformasi Pemilu 2024 Masif, Namun Masih Dinamis
Sudah berulang kali Marine Le Pen mengungkap kebencian terhadap muslim. Hal ini ia lakukan untuk merebut suara dari para islamophobia di Perancis. Apa yang dilakukan Le Pen itu sejatinya sangat mengerikan.
Kebayang gak kalau politisi macam begitu hidup di Indonesia? Bagaimana jika ada politisi yang bicara blak-blakan ingin merazia orang yang memakai kalung salib? Bagaimana jika ada capres yang ingin meniadakan lonceng gereja, meniadakan acara bakar dupa di vihara karena dianggap menyebabkan polusi udara?
Setau gue, belum ada politisi Indonesia yang sekonyol itu. Namun kita mesti waspada, karena bibitnya sudah mulai tumbuh walau masih malu-malu.
Pilpres Perancis adalah contoh politik identitas yang dimainkan dengan sangat culas. Beruntung Emmanuel Macron yang berhaluan sekuler liberal kembali menjadi pemenang dengan prosentase raupan suara sebesar 58,2%. Jika Le Pen yang menang, tentu Ousmane Dembele akan kebingungan. Karena winger Barcelona asal Perancis itu memiliki istri keturunan Maroko yang berhijab. Keluarga Zinedine Zidane dan Karim Benzema sudah pasti was-was jika Le Pen jadi presiden.
Akan jadi apa Perancis jika presidennya rasis? Smboyan Liberte, Egalite, Fraternite sudah barang tentu tak lagi eksis.
Ruby Kay
Editor : Pahlevi