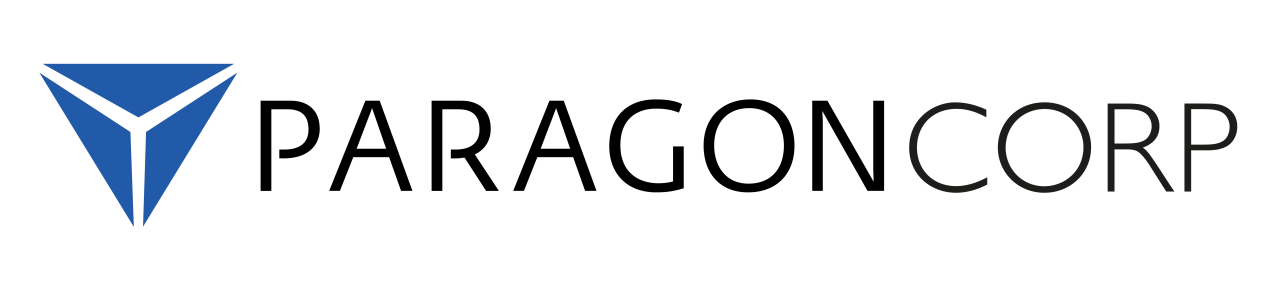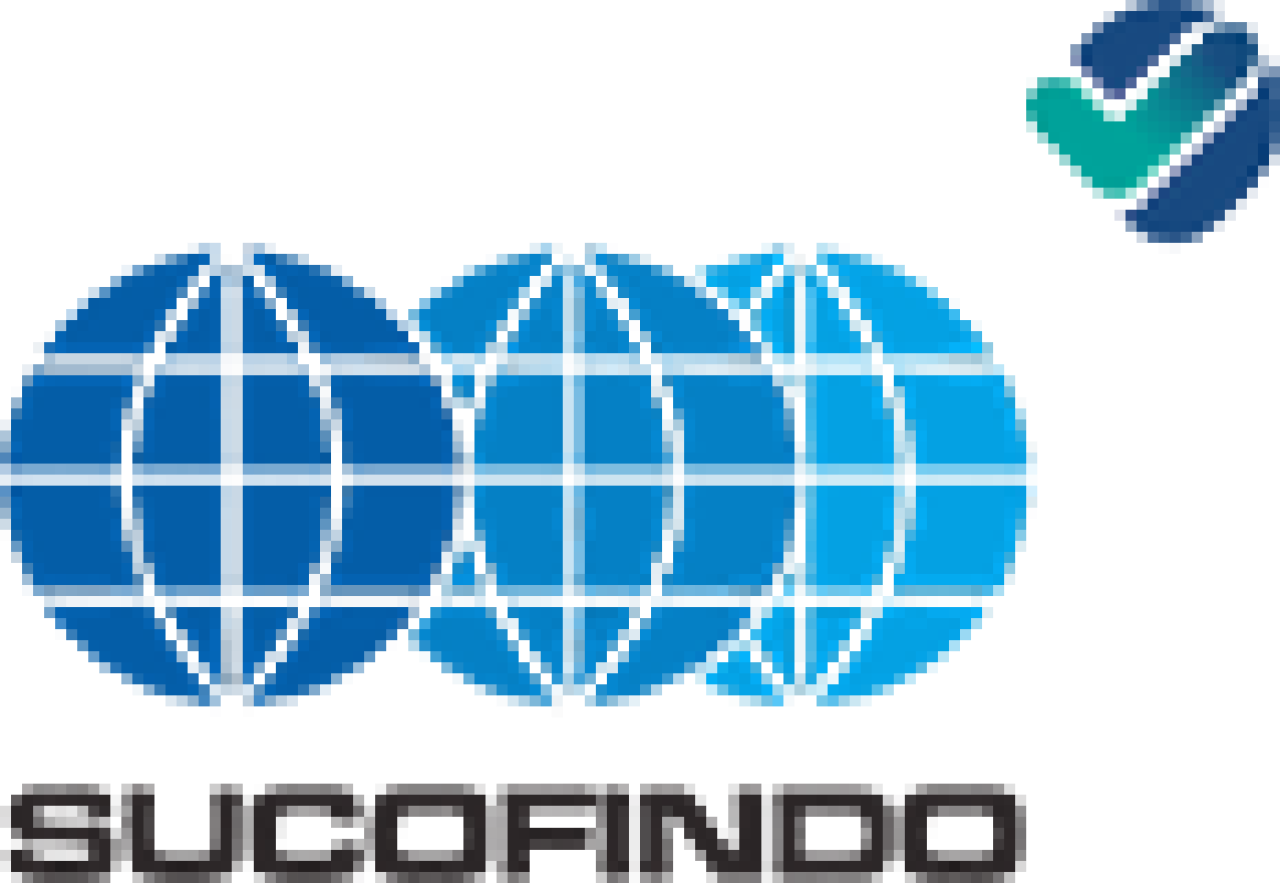Optika.id - Pakar Hukum yang juga Ketua Departemen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Zainal Arifin Mochtar menyebut dalam Undang-Undang IKN (Ibu Kota Negara) setidaknya terdapat tiga kecacatan. Salah satunya cacat moralitas konstitusional.
"Melihat fakta hukum yang ada bahwa proses pembentukan UU IKN yang dilakukan secara cepat (fast track), yang mana proses pembentukannya dilakukan secara 'tergesa-gesa' atau 'ugal-ugalan' telah banyak melanggar aspek prosedural (by pass law-making procedures) dan/atau dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipasi," kata Zainal seperti dilansir detik, Selasa (24/5/2022).
Baca Juga: Jokowi Soal Pindah ke IKN: Pindah Ibu Kota Jangan Dikejar-kejar
Hal itu disampaikan dalam keterangan ahli dalam sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tertuang dalam paper dari kuasa hukum pemohon. Zainal memaparkan sejumlah poin kekurangan dan cacat dalam pembentukan UU IKN itu.
"Proses legislasi seperti ini memenuhi kriteria sebagai praktik abuse of the legislation process. Dengan demikian, proses pembentukan UU IKN adalah inkonstitusional prosedural," katanya.
Selain itu, Zainal menyatakan, melihat fakta hukum minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan UU IKN, sudah sebaiknya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa para pembentuk undang-undang (DPR bersama pemerintah) telah melakukan pelanggaran konstitusional. Sebab, tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menfasilitasi dan/atau membuka ruang partisipasi publik secara luas dan secara khusus kepada masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap pemindahan Ibu Kota Negara.
"Seperti halnya kasus pemindahan Ibu Kotamadya Matatiele di Afrika Selatan," tandasnya.
Kesalahan UU IKN lainnya adalah proses pembentukan UU IKN (baik secara formal maupun material) telah melanggar prinsip nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional.
"Baik yang sudah dirumuskan dalam konstitusi maupun nilai-nilai konstitusional yang hidup (living constitution)," jelasnya
Menurut Zainal, konstitusionalitas proses pembentukan undang-undang bukan hanya menyangkut persoalan prosedural (konstitusionalitas formil) dan substantif (konstitusional material) saja. Tetapi konstitusionalitas pembentukan suatu undang-undang dapat dilihat lebih dari perspektif tersebut, termasuk mencakup nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional yang tersirat di dalam konstitusi (UUD 1945).
"Pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional haruslah digali dengan berbagai pendekatan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara," tukasnya.
Pendekatan ini dapat dijadikan dasar penilaian untuk menilai apakah undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional.
"Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas dan pelindung konstitusi (konstitusionalitas), dapat melakukan penegakan supremasi hukum melalui proses pengujian konstitusionalitas dengan pendekatan nilai-nilai konstitusional dan moralitas konstitusional untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang," terangnya
Diketahui, judicial review itu diajukan oleh Poros Nasional Kedaulatan Rakyat (PNKR). Selain itu, judicial review ini juga diajukan oleh banyak kalangan dan kelompok masyarakat. Dari sopir angkot, guru, pensiunan BUMN, Jenderal TNI (Purn), tokoh agamawan, hingga profesor.
UU IKN Cacat Formil
Hal senada dikatakan oleh Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof Susi Dwi Harijanti SH LLM PhD. Dia menilai UU IKN telah cacat formil. Salah satunya tidak menyerap aspirasi masyarakat yang terdiri atas hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapat penjelasan.
"Pertama dari aspek narasumber yang diundang, pembentuk UU No 3 Tahun 2022 telah gagal untuk meyakinkan masyarakat bahwa partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas," terangnya beberapa waktu yang lalu.
Kedua, platform digital berupa website dan YouTube yang lebih banyak digunakan sebagai penyebarluasan informasi. Hak-hak prosedural membutuhkan lebih dari sekadar mengunggah di website ataupun di kanal YouTube. Untuk sebuah rancangan undang-undang yang bersifat rumit dan kontroversial, masyarakat haruslah diberi kesempatan untuk memberikan masukan, kritik, dan bahkan proposal, yang kesemuanya harus direspons secara memadai oleh pembentuk undang-undang.
"Bahkan untuk rancangan undang-undang semacam ini, proses perdebatan di badan perwakilan tidak boleh diakselerasi," tegas Prof Susi.
Ketiga, dalam perdebatan di DPR perlu diperhatikan relasi antara mayoritas dan 'oposisi'. Misalnya, apakah para narasumber diajukan oleh mereka yang berasal dari mayoritas ataukah pihak oposisi diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan narasumber?
"Apalagi jika rapat-rapat pembahasan banyak yang bersifat tertutup atau lebih banyak melakukan lobi-lobi politik yang sudah barang tentu tidak dapat dihadiri oleh masyarakat," tukasnya.
Agenda Politik Terselubung
Prof Susi juga membeberkan berbagai alasan pemindahan ibu kota negara (IKN) di berbagai negara di belahan dunia. Ada yang berdasarkan alasan keamanan, tapi juga ada alasan politis menjauhkan rakyat dengan penguasa. Maksud itu disebutnya sebagai agenda politik terselubung atau 'hidden political agenda'.
"Ibu kota negara sering kali merupakan pusat dari gerakan masyarakat sipil dan tempat bergejolaknya protes dari masyarakat. Bahkan sejarawan Inggris Arnold Toynbee menyebut ibu kota sebagai 'the powder kegs of protest'. Maka dari itu, menurut ahli politik Jeremy Wallace, pemerintah otoriter akan menggunakan pemindahan ibu kota negara sebagai taktik segregasi dalam rangka mengasingkan gerakan masyarakat sipil yang awalnya berpusat di ibu kota negara yang lama, sehingga menjadi berjarak jauh dengan pusat pemerintahan yang berada di ibu kota yang baru," katanya.
Prof Susi menyitir pendapat Vadim Rossman, yakni tugas utama ibu kota negara adalah untuk memvisualisasikan dan mempresentasikan bangsa ke seluruh dunia. Dengan kata lain, ibu kota negara mewakili citra ideal dari suatu negara dan merupakan miniatur dari sebuah negara. Ahli sejarah Andreas W Daum berpendapat bahwa terdapat empat fungsi ibu kota bagi sebuah negara, yakni:
(1) fungsi administrasi,
(2) fungsi penunjang integrasi bangsa,
(3) fungsi simbolisasi bangsa, dan
(4) fungsi pelestarian nilai, budaya, dan sejarah bangsa.
"Berdasarkan pendapat tersebut, ibu kota negara tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan saja, akan tetapi berfungsi pula sebagai manifestasi identitas bangsa," ucap Prof Susi.
Menurut Vadim Rossman, agar fungsi ibu kota sebagai penunjang integrasi bangsa dapat terwujud secara optimal, ibu kota harus dihasilkan melalui kompromi dari elemen-elemen bangsa yang terdiri atas etnis, agama, dan suku yang berbeda. Hal tersebut akan membuat ibu kota menjadi alat pemersatu dari perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu bangsa.
"Montesquieu dalam bukunya 'My Thoughts (Mes Pensées)' menggambarkan pula ibu kota sebagai kota yang menciptakan 'general spirit' bagi sebuah bangsa," tutur Prof Susi.
Baca Juga: Muhammadiyah Ingin Dirikan Kantor hingga Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di IKN
Dalam beberapa kasus, dijumpai kondisi ketika ibu kota suatu negara tidak dapat menghadirkan fungsi-fungsi ibu kota tersebut. Misalnya ibu kota yang lama dianggap menjadi sumber perpecahan dan secara geografis rentan terhadap bencana alam, sosial, ataupun serangan militer. Maka dari itu, beberapa negara di dunia memutuskan untuk memindahkan lokasi ibu kotanya dengan harapan ibu kota baru dapat lebih baik daripada ibu kota sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Namun Vadim Rossman mengingatkan bahwa dapat saja pemindahan ibu kota dilakukan karena adanya 'hidden political agenda', misalnya dalam rangka memperkuat kekuatan politik suatu rezim," jelasnya.
Rossman mengemukakan tiga bentuk hidden political agenda yang mungkin terjadi yakni:
1) mengasingkan atau memarginalisasi gerakan protes,
2) Homogenisasi etnis penduduk ibu kota, dan
3) pemindahan ibu kota ke wilayah asli penguasa.
Ibu kota negara sering kali merupakan pusat dari gerakan masyarakat sipil dan tempat bergejolaknya protes dari masyarakat, bahkan sejarawan Inggris Arnold Toynbee menyebut ibu kota sebagai 'the powder kegs of protest'. Hal tersebut pernah terjadi di Prancis pada 1871, ketika terjadi protes besar-besaran di Paris.
"Pemerintah Prancis memindahkan ibu kota sementara ke Versailles untuk menghindari protes. Begitu pula dengan Myanmar, pemerintah otoriter di sana memindahkan ibu kota negara dari Yangon ke Naypyidaw karena Kota Yangon merupakan pusat gerakan dari para biksu yang kerap memprotes pemerintah," kata Prof Susi.
Agar pemindahan ibu kota benar-benar dilakukan untuk kepentingan negara dan bangsa, terdapat sejumlah pertanyaan yang dibuat oleh Vadim Rossman, yakni:
1. Di mana lokasi yang paling aman untuk dijadikan ibu kota negara.
2. Di mana lokasi yang paling efektif secara ekonomi dan administratif untuk mencapai tujuan negara.
3. Di mana lokasi yang dianggap paling adil bagi berbagai kelompok masyarakat.
4. Lokasi mana yang paling organik, autentik, dan sesuai dengan identitas dan kedaulatan bangsa yang diwakili oleh negara.
"Mengingat fungsi fundamental ibu kota negara bagi sebuah bangsa, proses pembuatan keputusan untuk memindahkan ibu kota harus mencerminkan 'fundamental decision of a nation'. Hal tersebut juga sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi pemindahan ibu kota negara yang hanya dilatarbelakangi oleh hidden political agenda," tegas alumnus Doktoral The University of Melbourne ini.
Prof Susi memberikan beberapa contoh:
Baca Juga: Puan Maharani Setelah di IKN: Rumah Oke, Tidur Nyenyak
Korea Selatan
Di Korea Selatan, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada 2005 memutuskan rencana perpindahan ibu kota dari Seoul adalah inkonstitusional. Hakim konstitusi di Korea Selatan berpendapat bahwa Seoul sebagai ibu kota merupakan constitutional custom yang merupakan bagian dari konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution).
Konstitusi Korsel memang tidak menyatakan secara tegas bahwa Seoul merupakan ibu kota Korea. Namun praktik ketatanegaraan telah mendudukkan Seoul sebagai ibu kota Korea bahkan semenjak Dinasti Joseon. Artinya, Seoul sudah menjadi ibu kota Korea selama 600 tahun lamanya. Karena itu, Seoul sebagai ibu kota Negara dianggap sebagai constitutional custom oleh hakim konstitusi Korea Selatan, dan karena itu pemindahan ibu kota negara harus berasal dari fundamental decision of the people with respect to the nation.
"Hakim konstitusi Korea Selatan berpendapat, karena Seoul sebagai ibu kota merupakan muatan dari konstitusi tidak tertulis, pemindahan ibu kota seyogianya dilakukan dengan amandemen konstitusi," urai Prof Susi.
Sesuai dengan Pasal 130 Konstitusi Korea Selatan, untuk mengubah konstitusi, harus dilakukan referendum terlebih dahulu. Selain melalui amandemen konstitusi secara formal, constitutional custom tersebut dapat hilang kekuatan hukumnya apabila kehilangan dukungan secara nasional. Namun, menurut hakim konstitusi Korea Selatan, hal tersebut tidak terjadi dan tidak dapat dikonfirmasi pada saat itu karena tidak dilaksanakannya referendum atau tidak terjadi gejolak sosial sama sekali yang menyebabkan ibu kota harus dipindahkan.
"Terlebih lagi proses pembahasan undang-undang terkait pemindahan ibu kota di Korea Selatan hanya berlangsung selama tiga bulan," tegasnya.
Brasil
Praktik mendudukkan status ibu kota sebagai bagian dari problematika konstitusional juga dapat dijumpai di Brasil. Rencana pemindahan ibu kota di Brasil bukan merupakan keinginan presiden semata.
Pemindahan ibu kota di Brasil merupakan amanat Peraturan Peralihan Konstitusi Brasil 1946. Di dalam Pasal 4 Peraturan Peralihan Konstitusi Tahun 1946 tersebut diperintahkan bahwa 'the capital of the Union shall be moved to the central highlands'. Setelah berhasil melakukan perpindahan, ibu kota baru Brasil, yakni Brasillia, pun akhirnya diakui melalui Pasal 18 Ayat (1) Konstitusi Brasil tahun 1988, yang berbunyi:
The federal capital is Brasília.
"Dari praktik di Korea Selatan dan Brasil tersebut, kita dapat memetik pelajaran bahwa negara-negara tersebut mendudukkan ibu kota negara sebagai materi muatan dari konstitusi, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, karena adanya sebuah kesadaran bahwa ibu kota merupakan identitas bangsa yang fundamental. Akibatnya, keputusan akan pemindahannya harus benar-benar disepakati oleh seluruh warga negara," tutup Prof Susi dalam keterangan tertulisnya terkait sidang judicial review UU IKN dalam perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (12/5/2022).
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi