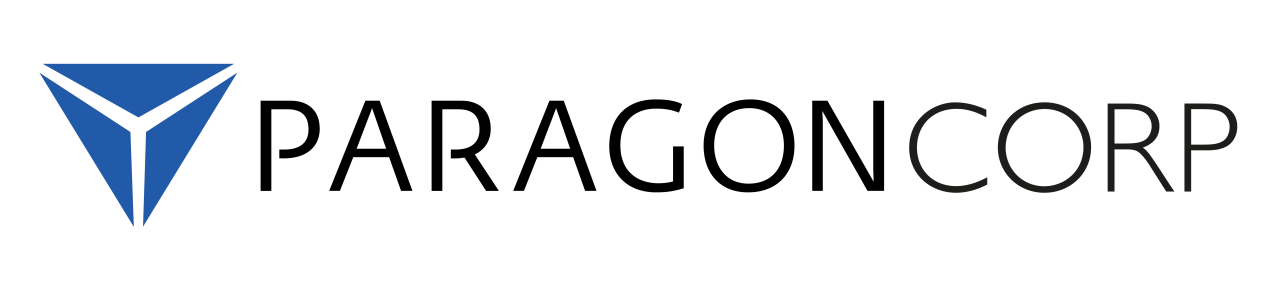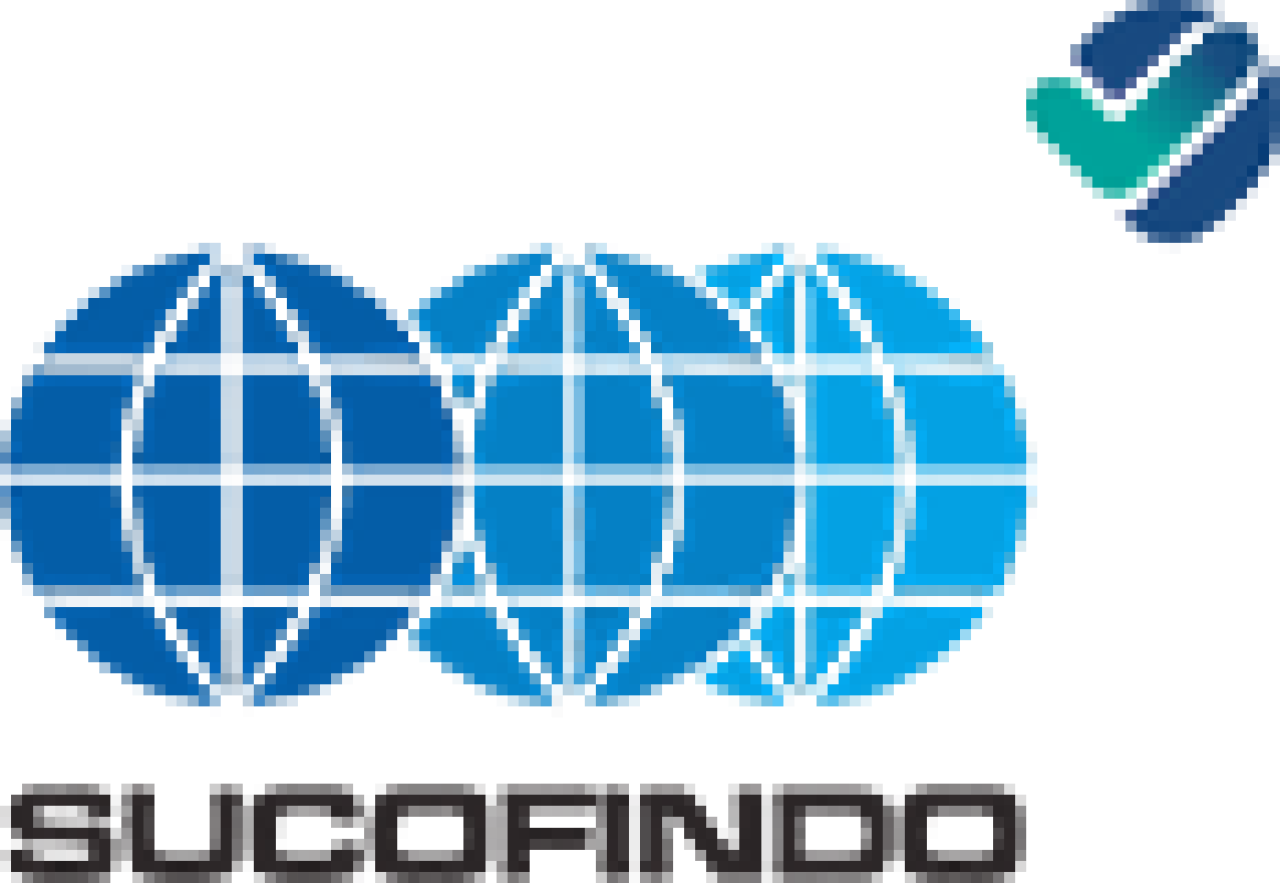Optika.id - Pada tahun 1940-an, India masih berupa kesatuan geografis-antropologis yang mencakup seluruh wilayah Asia Selatan. Selama berabad-abad, kota-kota metropolis raksasa seperti Bombay, Madras, Delhi dan Calcutta serta kota-kota dengan aktivitas produksi berskala lebih kecil seperti Karachi, Lucknow, Dacca dan Lahore mengalami dinamika perubahan sosial politik-ekonomi yang sangat kompleks.
Baca Juga: Konflik Palestina dan Israel Kembali Pecah, Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia?
Kantor dagang, bank, restoran, gedung bioskop, warung kopi dan event bazaar dapat mudah dijumpai. Bangunan religius seperti masjid dan kuil bertebaran sepanjang gang dan jalan raya yang padat. Sekolah, perguruan tinggi dan universitas bermunculan seiring dengan perkembangan intelektual terdidik.
Surat kabar, majalah mode, buku ilmiah dan novel fiksi bersaing dalam ajang kepopuleran. Profesi baru memperluas lapangan pekerjaan mengikuti tantangan kemajuan. Sarana transportasi dari mobil sampai kereta api lalu lalang melintasi jalurnya.
Yasmin Khan dalam buku The Great Partition: The Making of Indonesia and Pakistan menyebut para wanita di Punjab mempunyai hobi baru yaitu bepergian tanpa kerudung, memakai sepatu hak dan berbahan sintesis. Pasar menjual kain bermotif cerah, permen, perhiasan emas, daun tembakau bahkan cangkir keramik khusus minum teh. Kota-kota perniagaan menyediakan sektor jasa sedangkan daerah hinterland mendukungnya dengan mengirim produk hasil pertanian.
Sebagaimana negara-negara Dunia Ketiga lainnya, India menghadapi persoalan urbanisasi yang membanjiri kota-kota metropolitan sehingga menciptakan pemukiman kumuh berpenduduk miskin. Kesulitan hidup di pedesaan terjadi seiring menyusutnya lahan pertanian. Akibatnya banyak petani (tanpa lahan) terpaksa mencari pekerjaan kasar di kota-kota besar.
Kehidupan petani migran itu makin terpuruk karena perang melanda beberapa tempat tertentu yang pastinya cukup dashyat menggocang perekonomian. Namun, perang juga memberi keuntungan pada kota metropolis Kanpur yang menerima permintaan kapas, wol, goni dan gula yang cukup besar sehingga menyedot ribuan buruh migran sepanjang tahun 1941 sampai 1951.
Baca Juga: Kiprah Politik Moh. Ali Jinnah
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Usai perang, banyak buruh migran kehilangan pekerjaannya dan pengangguran mencapai tingkat yang mengerikan. Mereka kembali ke kampung halaman untuk beternak ataupun membudidayakan ikan. Yang tersisa memilih menjadi pekerja lepas yang hidup semrawut di pinggiran kota.
Pada tahun 1940-an, sekitar 40% petani tidak memiliki lahan pertanian sehingga menyiasati dengan sepenuhnya bergantung pada pekerjaan musiman. Potret kehidupan pinggiran perkotaan menampilkan banyak orang bertelanjang kaki, berpakaian compang camping serta menderita sakit karena bertahan hidup dengan satu kali makan dalam sehari. Pasar merupakan ladang bagi orang-orang kelaparan.
Mereka mencari nasi basi serta sag (bayam) dan mahuwa (biji yang dapat dimakan dan bunga) yang tidak laku. Kebutuhan pokok seperti roti, gandum, biji-bijian, kain dan minyak mengalami kelangkaan. Pada tahun 1943, terjadi kelaparan hebat yang menimpa masyarakat Bengali.
Baca Juga: Menuju Kemerdekaan Pakistan
Pemerintah tidak mampu mengatasinya hingga membiarkan mereka mati kelaparan. Tahun 1946, terjadi krisis pangan yang memicu penyelewengan semacam menjual di pasar gelap. Orang-orang miskin yang kelaparan memberontak, buruh mengadakan protes dengan menolak memindahkan karung gandum ke truk bahkan merobek karung dengan tangan mereka. India pun berada di ambang kehancuran.
Rushdy Hoesein dalam Terobosan Soekarno Dalam Perundingan Linggarjati, dikutip Optika.id, Jumat (23/6/2023) menjelaskan jika saat itu politisi India mengatasi bencana kelaparan dengan memanfaatkan hubungan diplomatik. 19 Mei 1946, Perdana Menteri Indonesia, Sjahrir menyerahkan keranjang penuh berisi padi kepada H.I. Punjabi secara simbolis. 1 Agustus 1946, perjanjian bilateral antara India dan Indonesia resmi terjalin bersama pengiriman bantuan beras.
Editor : Pahlevi